Irfan
kelihatan murung, melayan kenangan lampau yang menyakitkan hatinya. Irfan, anak sulong dari empat beradik itu
kelihatan kusut dan serabut. Banyak
perkara yang berlegar di kotak fikirannya.
Antara tanggungjawab dan desakan hidup, yang mana harus di
utamakan. Jari-jemarinya mencapai
ranting kering yang bertaburan di bawah pokok tempat dia melepaskan keluhan,
lalu di patah-patahkannya. Sesekali
Irfan mengeluh dengan nasib yang menimpa dirinya. Baginya, remaja yang seusianya tidak wajar
menanggung beban yang berat seperti yang di tanggungnya. Masih terngiang-ngiang suara ayah
memarahinya.
“Irfan, apa
nak jadi dengan kau ni? Ayah suruh kau pergi sekolah untuk belajar, bukan untuk
jadi samseng. Kau tak kasihankan ayah
dengan mak ke? Kita orang susah Irfan, ilmu lah yang boleh ayah dengan mak
bekalkan untuk kau bila kami tak ada nanti.”
Ayahnya, Pak Ramlee tidak pernah berhenti menasihati anak lelakinya itu
dengan harapan Irfan akan berubah dan menjadi anak yang bertanggungjawab. Namun, Irfan tidak pernah mengendahkan
nasihat ayahnya itu. Jauh lamunannya
mengimbau kembali saat ayahnya masih bersama keluarganya. Namun kini semuanya sudah berubah..
“Woi,
Irfan. Jauh nampak kau mengelamun. Dah sampai ke bulan ke?” sergah Amar, kawan baik Irfan sejak di bangku
sekolah rendah lagi. Mereka tetap
bersama dalam banyak hal.
“Kau ni Amar,
kalau kau datang bagi salam kan elok sikit.
Kau nak aku mati macam bapak aku ke?”
Marah Irfan sambil bangun dan menyapu pasir yang melekat di seluarnya.
“Kau ni sejak
bila jadi ustaz hah? Selalu aku
sergah-sergah kau tak ada pulak kau marah kan.
Hari ni lain macam pulak aku tengok.
Seram sejuk dibuatnya.” Amar
sempat melawak walaupun wajah Irfan mencuka tanda protes. Irfan tidak mahu cakap banyak, lantas
meninggalkan Amar terpinga-pinga. Amar
yang kelihatan baru tersedar dari tidur lantas berlari membontoti Irfan.
Malam
kelihatan kelam tanpa bintang yang menemani seperti kebiasaannya. Hanya kelihatan bulan yang malu-malu
menampakkan wajahnya. Irfan termanggu di
tangga sambil mendongak bintang. Entah
kenapa sejak kematian Pak Ramlee, Irfan lebih banyak termenung dan menghabiskan
masa di rumah. Di sekolah juga perangainya
tidak seperti selalu. Tiada lagi pelajar
nakal yang selalu membuat onar dan memeningkan kepala guru.
Mak Miah
perasaan akan perubahan anak sulongnya itu namun tidak pula bertanya kerana
sudah masak dengan perangai panas baran Irfan.
Mak Miah berlalu ke dapur meyiapkan makan malam untuk anak-anaknya. Nasi yang hanya berlaukkan telur goreng,
pucuk ubi dan kicap sudah cukup menyelerakan mereka anak beranak yang kurang
serba-serbi apatah lagi sejak kematian suami sekaligus bapa kepada anak-anaknya. Bagi Mak Miah, kematian Pak Ramlee bagaikan
telah mencabut sebahagian nyawanya.
Begitu mendalam sekali kasih dan sayang Mak Miah terhadap arwah
suaminya.
Irfan hanya
memerhatikan gelagat emak dan adik-adiknya yang berada di dapur dari jauh. Sesekali pandangannya meliar memerhatikan
keadaan rumahnya. Begitu usang dan daif
sekali. apabila hujan, pasti ada air
yang menitis dari bumbung yang bocor.
Hanya dia yang tidak tahan dengan keadaan tersebut, namun tidak pula
bagi adik-adiknya yang seperti redha dan seakan faham dengan kedaifan dan
kesusahan hidup mereka.
“Mak, cikgu
Ilham minta yuran sekolah, tapi Ilham dah cakap kat cikgu nanti mak ada duit
mak akan bayar yuran sekolah tu.”
Lamunan Irfan terhenti mendengarkan kata-kata adiknya Ilham yang belajar
di tingkatan tiga. Begitu tenang Ilham
menyuarakan kata-kata supaya emaknya tidak terlalu memikirkan hal itu. Lama Irfan memandang wajah ibunya yang
kelihatan serba salah. Barangkali
memikirkan cara untuk mendapatkan duit bagi membayar yuran sekolah. Bukan sahaja yuran sekolah Ilham sahaja yang
belum di bayar, malah adik-adiknya Iman dan Intan juga belum berbayar.
“Ilham
beritahu kat cikgu, bulan depan mak bayar yuran sekolah ye.” Emak berjanji dengan Ilham walaupun dia belum
pasti dapat tunaikan atau pun tidak.
“Cikgu tak ada tanya ke yuran sekolah Iman dengan Intan?” emak mula menyoal adik-adiknya. Iman yang belajar darjah enam dan Intan
darjah tiga. Masing-masing
menggeleng. Kelihatan emak menarik
nafas lega. Irfan yang hanya mendengar
bait-bait perbualan mereka hanya mampu mengeluh. Dia sendiri pun masih banyak hutang dengan
pihak sekolah, lagi lah dia sekarang di tingkatan lima. Tidak lama lagi Irfan bakal menduduki
peperiksaan SPM. Walaupun Irfan seorang
budak yang nakal, namun dia merupakan pelajar pintar.
Pagi itu Irfan
kesekolah seperti biasa, namun kali ini niatnya sudah berubah. Dia ingin mengubah nasib keluarganya. Dia ingin belajar bersungguh-sungguh dan
mendapat keputusan yang boleh membanggakan ibunya. Guru-guru di sekolah kaget dengan perubahan
Irfan, namun tidak pula disoal kenapa.
Bagi mereka semua itu tidak penting, asalkan Irfan tidak lagi membuat
onar disekolah seperti yang selalu dilakukannya.
“Irfan, malam
ni lepak macam biasa nak tak?” ajak Amar
usai sesi pembelajaran. Namun Irfan
hanya menggelengkan kepala. Amar pelik
dengan kelakuan Irfan sejak belakangan ini.
Namun, Irfan tidak pula menjelaskan apa-apa, kerana baginya Amar yang di
lahirkan dalam keluarga yang serba serbi mewah tidak akan pernah faham dengan
penderitaan yang ditanggung keluarganya.
Irfan bangun dan berjalan menuju ke arah Amar dan menepuk bahunya lembut
lantas berlalu pergi.
Amar tetap
tidak berpuas hati dengan perubahan Irfan, dia cuba mengekori Irfan dan apa
yang memeranjatkan Amar bila melihat
Irfan yang masih berseluar sekolah bekerja di bengkel tidak jauh dari
rumahnya. Amar hairan namun dibiarkannya
sahaja. Begitulah rutin Irfan setiap
hari semenjak kematian ayahnya, Pak Ramlee.
Lewat malam
barulah Irfan pulang kerumah ketika emak dan adik-adiknya sudah tidur. Mak Miah tidak tahu kemana perginya anak
sulongnya itu, namun dia tidak hairan kerana begitu lah kebiasaan Irfan ketika
arwah suaminya masih lagi ada lagi. Mak
Miah membiarkan sahaja anaknya itu dengan menganganggap anaknya sudah besar dan sudah tahu membezakan
antara yang baik dan juga buruk.
Pagi itu
semasa bersarapan, Iman bersuara terketar-ketar. Baginya ingin diluah mati bapak, ingin
ditelan mati emak. Namun digenggamkan
tangannya mengumpul keberanian. Waluapun
baru sahaja berusia dua belas tahun namun dia sudah memahami kesusahan yang
ditanggung ibunya.
“Mak,cikgu Man
minta man bayar yuran sekolah, dia cakap hari ni hari terakhir kena bayar. Dalam kelas Man, Man sorang je belum bayar
mak.” Lama Iman merenung wajah sugul
ibunya. Irfan yang mendengar perbualan
tersebut melangkah kedapur dan menghadap Iman.
“Berapa yuran
kau belum bayar.” Irfan memang tak
pernah berlembut dengan adik-adiknya.
Dia tidak mahu mereka besar kepala dan tidak menghormatinya. Direnung tajam mata Iman. Iman yang gerun lantas menundukkan mukanya.
“Seratus lima
puluh abang.” Jawab Iman lemah sambil
menguis-nguis kakinya kelantai. Irfan
menyeluk saku dan mengeluarkan not lima puluh lima keping. Tiga keping diberikan kepada Iman, dua keping
lagi dihulurkan kepada ibunya. Lantas
Irfan beredar. Seisi rumah
terpinga-pinga dengan tindakan Irfan.
Mak Miah pula hanya mampu tersenyum.
Naluri ibu dapat merasakan anaknya sudah berubah. Namun tidak pula bagi pandangan adik-adiknya.
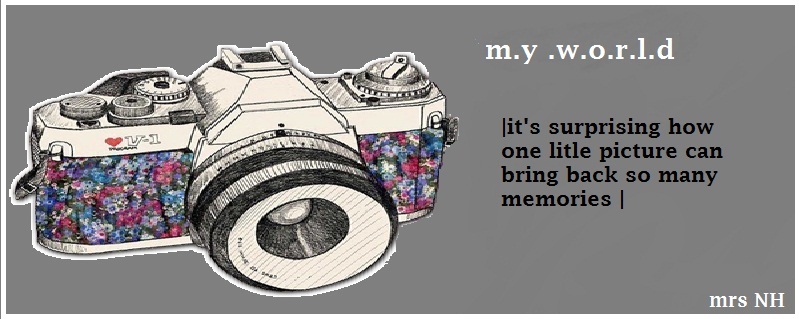

No comments:
Post a Comment